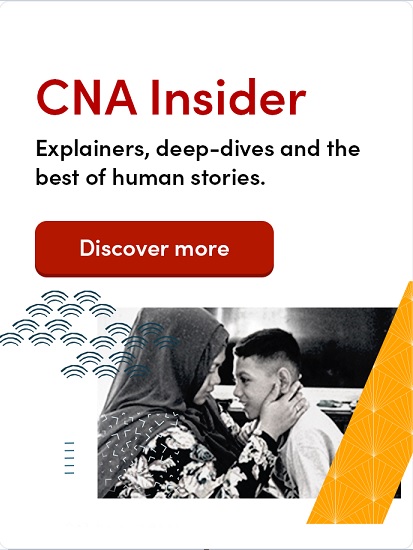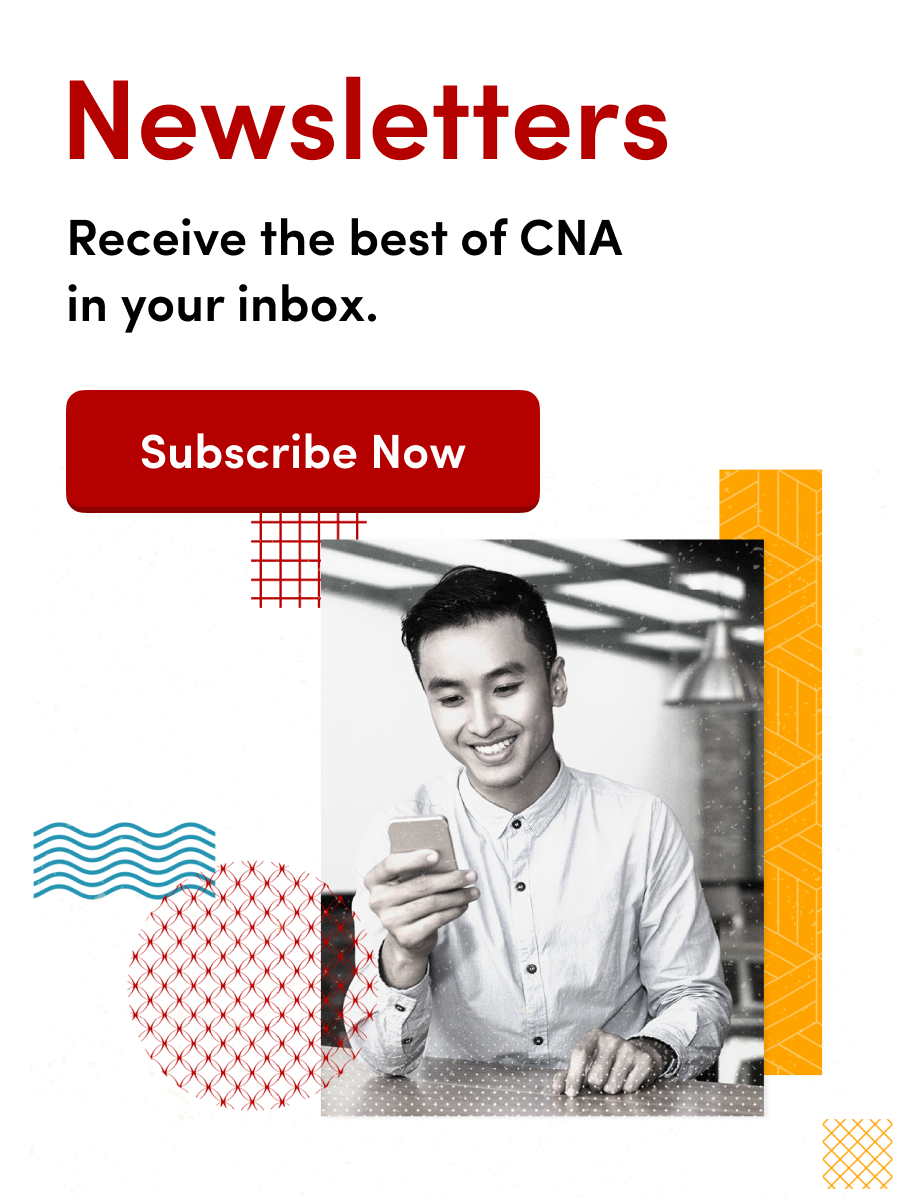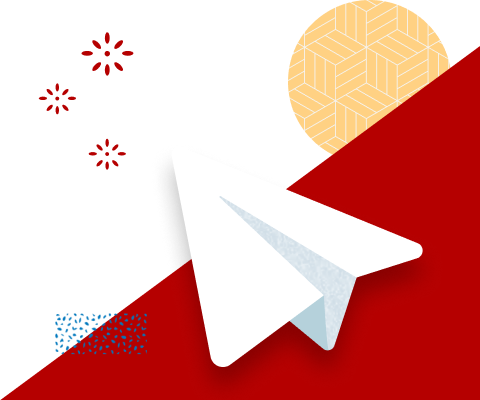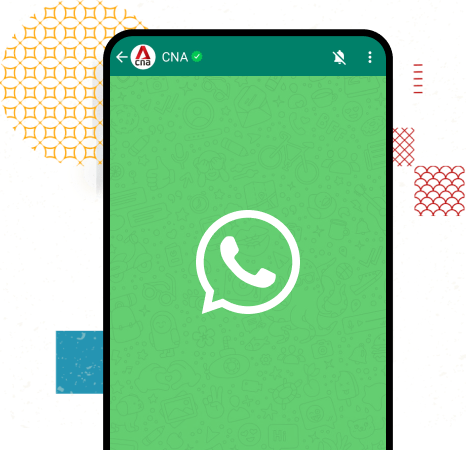‘Buka gemboknya’: Sejak pandemi COVID-19 makin banyak orang dengan gangguan jiwa hidup dipasung
Menyambut Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada 10 Oktober, CNA menelaah bagaimana ribuan penduduk di Indonesia hidup dipasung karena mengalami gangguan jiwa. Target pemerintah mengakhiri praktik pemasungan pada 2019 masih jauh dari tercapai.

KARANGASEM, Bali: Gunung Agung menjulang megah di sisi timur Pulau Bali, tepatnya di Kabupaten Karangasem.
Gunung berapi tertinggi di Pulau Dewata tersebut – dengan puncak 3.000 meter di atas permukaan laut – memang mempunyai keagungan yang tak bisa dipungkiri siapapun yang mengunjungi Karangasem.
Yasa tinggal di lereng Gunung Agung, namun keindahan gunung ini tak pernah nampak dari tempat ia menghabiskan waktunya sehari-hari.
Lelaki berumur 37 tahun ini hidup dalam pasungan di sebuah gubuk reyot yang terbuat dari daun kelapa. Pemandangan gunung sama sekali tak nampak dari ruangannya yang gelap.
“Aku haus!”, teriaknya ketika CNA mengunjungi gubuk ini bersama ibunya, Seken, pada bulan Agustus lalu.
Pergelangan kaki kiri Yasa terikat rantai. Ia menghabiskan waktunya setiap hari berbaring di ranjang bambu tua yang cuma dilapisi kasur tipis kotor.
Yasa dipasung oleh keluarganya sendiri karena mereka menganggap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) seperti dirinya membahayakan orang lain.
“Dia sering memukul saya dan ayahnya,” kata Seken pada CNA waktu ditanya kenapa mereka memutuskan untuk memasung Yasa.
“Kami cuma bisa berusaha menghindar waktu Yasa masih bebas. Saya dulu sering bersembunyi di rumah anak mantu saya,” kenang Seken yang berumur 65 tahun.

Kementerian Kesehatan mengakui bahwa di seluruh Indonesia ribuan ODGJ masih hidup dipasung.
Pemerintah meluncurkan beberapa program untuk menghentikan praktik pemasungan, dengan target mengakhirinya pada tahun 2019.
Namun menurut Kemenkes, program-program tersebut susah berjalan karena minimnya akses pelayanan kesehatan, stigma terhadap ODGJ, rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa, dan kemiskinan.
Pandemi COVID-19 makin membatasi akses pelayanan kesehatan. Di samping itu, ada kekhawatiran bahwa virus itu dapat disebarkan oleh orang-orang dengan penyakit mental. Akibatnya, kasus pemasungan naik lagi.
Menurut data Kemenkes, terdapat sekitar 6.500 kasus pemasungan pada 2020, naik dari 5.000 kasus pada 2019.
PERANG MELAWAN PASUNG
Di Indonesia, menurut aturan Kemenkes tahun 2017 untuk menanggulangi praktik ini, pemasungan didefinisikan sebagai pembatasan gerak ODGJ.
Bentuk pembatasan yang paling sering dijumpai adalah merantai ODGJ atau mengurung mereka di ruangan sempit.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya, mengatakan pemasungan sulit dihapuskan karena praktik ini tidak ditangani secara komprehensif dengan melibatkan semua sektor. Pandemi COVID-19 pun ikut meningkatkan jumlah kasus.
“Kasus pemasungan jadi naik selama pandemi karena akses masyarakat ke layanan kesehatan jiwa makin tertutup. Prioritas pemerintah menangani pandemi sehingga fasilitas dan layanan kesehatan jiwa banyak yang dialihgunakan untuk itu,” jelasnya.
Masyarakat, bahkan keluarga ODGJ, juga masih banyak yang belum memahami penyebab gangguan jiwa maupun cara penanganannya.
Yasa, yang hanya mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar, dipasung secara tidak terus-menerus selama 20 tahun terakhir.
Waktu remaja ia bekerja di sebuah galeri seni hingga suatu hari ia mengalami trauma mental.
“Saya dulu kerja. Saya masih ingin kerja lagi,” katanya kepada CNA.
Namun waktu ditanya trauma kejiwaan apa yang menimpanya, ia hanya menjawab sedih: “Saya tidak tahu. Ingatan saya kabur.”

Ingatan Ibu Yasa, Seken, yang mempunyai 10 anak, tentang trauma kejiwaan anak bungsunya juga kabur. Ia hanya ingat bahwa Yasa tiba-tiba sering bingung dan gelisah.
Yasa sempat dirawat beberapa kali di satu-satunya Rumah Sakit Jiwa di Bali. Namun tiap kali dia dipulangkan, ia akan kabur kemudian berkeliaran di Karangasem dan kadang tidak pulang ke rumah.
Karena itulah keluarganya yakin pasung adalah solusi bagi mereka karena dengan begitu Yasa tidak bisa melarikan diri dari rumah.
“Saya kasihan sama Yasa, tapi mau bagaimana lagi?” Seken mengatakan dalam bahasa Bali.

Yasa sekarang dirawat oleh psikiater Luh Ketut Suryani, pemilik Suryani Institute for Mental Health (Institut Kesehatan Mental Suryani) di ibukota Bali, Denpasar, kira-kira dua jam bermobil dari Karangasem.
Sukarelawan dari klinik Suryani mengunjungi Yasa secara berkala untuk memberinya obat-obatan dan sembako, karena ia berasal dari keluarga miskin dengan profesi serabutan.
Selain merawat Yasa, Seken juga harus menjaga suaminya yang sakit-sakitan.
Menurut pendapat Suryani, pemasungan sulit dihapuskan karena banyak orang di Indonesia yang masih mempercayai bahwa gangguan jiwa adalah “penyakit kutukan yang tidak ada obatnya.”
Beberapa orang juga mencoba untuk menyembuhkan sendiri orang yang mereka cintai tetapi tidak berhasil. Akhirnya mereka merasa putus asa.
MAKIN BURUK KARENA COVID-19
Made, 42 tahun, juga seorang ODGJ.
Ia tinggal di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, hanya 15 menit naik mobil dari daerah seni paling sibuk dan terkenal di Bali, Ubud.
Made dikurung di kamar sempit berukuran 10 meter persegi. Dari balik jeruji ia mengatakan kepada CNA bahwa ia sering merasa kesepian.
“Saya tidak bisa ketemu teman. Tidak bisa melihat cahaya luar,” kata Made.
“Tolong buka gemboknya,” kata Made sambil menunjuk gembok besi di pintu selnya.
Selama sembilan tahun Made dikunci di sel sempit ini, hanya sesekali dibiarkan keluar.
Ia sempat dibebaskan sebelum pandemi dan menghabiskan waktunya berkeliaran di jalanan di Abiansemal.

Waktu pandemi datang, penduduk sekitar takut Made akan ikut menyebarkan virus COVID-19.
Ayahnya, yang berumur 80-an tahun dan sakit-sakitan, memutuskan untuk mengurungnya lagi karena ia tinggal sendirian dan merasa tak mampu mengawasi Made.
Made sekarang berada di bawah pengawasan psikiater I Gusti Rai Putra Wiguna.
“Sulit untuk menghentikan pasung selama pandemi karena keluarga ODGJ juga stres.”
“Kemudian ada stigma bahwa ODGJ susah diberitahu untuk mengikuti protokol kesehatan COVID-19,” kata Wiguna.
Menurut survei Mediacorp, 36 persen penduduk Indonesia (dari sampel 1.000 orang) mengaku bahwa kesehatan jiwa mereka memburuk selama pandemi.
Dari 36 persen ini kebanyakan menyalahkan pembatasan sosial sebagai pemicu stres, termasuk kewajiban memakai masker, larangan bepergian, dan pembatasan interaksi sosial.
Terutama di Bali, yang ekonominya tergantung kepada pariwisata sehingga kehidupan terguncang hebat oleh pandemi, banyak masyarakat yang mengalami gangguan mental sehingga harus menjalani perawatan, kata Wiguna.
Menurut datanya, kasus bunuh diri di Bali naik sebesar 100 persen sepanjang pandemi.
Data dari klinik pencegahan bunuh diri tempat ia bekerja menunjukkan 68 kasus bunuh diri pada 2020, 124 pada 2021, dan 58 selama empat bulan pertama tahun 2022.
Akibatnya, menghentikan praktik pemasungan tidak lagi menjadi prioritas karena ada banyak masalah lain yang dianggap lebih genting dan harus segera ditangani.
Pada awal pandemi tenaga kesehatan juga kekurangan alat pelindung diri (APD) sehingga mereka tidak bisa lagi mengunjungi ODGJ di tempat tinggal mereka, jelas Wiguna.
Kepala Dinas Kesehatan Bali, I Nyoman Gede Anom, memberikan pendapat serupa.
Banyak penduduk di Bali kehilangan mata pencaharian mereka sehingga mengalami depresi, katanya.
Banyak orang yang terkena COVID-19 juga kemudian mengalami depresi, tambahnya.
“Di awal pandemi, masyarakat hidup dalam ketakutan. Karena belum ada vaksin, tidak ada imunitas.”
“Setiap kali ada yang kena (COVID-19), mereka stres. Dalam beberapa kasus, pasien di rumah sakit berteriak-teriak histeris karena ingin melarikan diri… karena mereka depresi,” ceritanya.
Menurut I Nyoman, jumlah tenaga kesehatan jiwa profesional di Bali sama sekali tidak memadai.
Data dari survei Mediacorp menunjukkan hanya 43 persen penduduk di Indonesia yang menganggap bahwa pelayanan kesehatan jiwa masyarakat sudah memenuhi standar.
PANTI DAN KLINIK SWASTA MENGAMBIL ALIH
Karena hanya ada sekitar 50 Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia dan kira-kira 1.000 psikiater untuk menangani 270 juta warga negara, banyak orang menggantungkan diri pada panti dan klinik swasta untuk merawat ODGJ di keluarga mereka.
Dalam survei Mediacorp, sekitar 48 persen responden menginginkan lebih banyak layanan kesehatan jiwa masyarakat di Indonesia, termasuk inisiatif kesehatan jiwa di tempat kerja serta layanan psikiatri dan psikologis.

Di Bekasi yang terletak di pinggiran Jakarta terdapat beberapa fasilitas swasta yang menangani ODGJ, salah satunya panti Al Fajar Berseri.
Pendiri Al Fajar, Marsan Susanto, 51 tahun, mengatakan ia baru menyadari panggilan hidupnya untuk merawat ODGJ waktu suatu hari menjumpai seorang ODGJ melahap nasi dari tong sampah yang dikerumuni lalat.
Marsan dulunya bekerja sebagai kusir dan tidak mempunyai latar belakang psikiatri sama sekali. Ia mendirikan pantinya yang dibiayai oleh donasi masyarakat pada tahun 2005.
Panti ini sekarang jadi tempat tinggal sekitar 500 ODGJ.
Dari semua itu, mereka yang dianggap tidak berbahaya dibebaskan untuk beraktivitas di dalam fasilitas berukuran 8.000 meter persegi tersebut. Namun mereka yang dianggap mengalami gangguan jiwa lebih parah ditempatkan di sebuah gedung berjeruji yang terpisah.
Kata Marsan, ada dua pasien yang dirantai karena mereka bertingkah laku agresif sejak dimasukkan ke Al Fajar.
Saat CNA mengunjungi panti ini di awal September, seorang lelaki kelihatan melempari Marsan yang sedang berdiri di depannya dengan kulit jeruk memakai tangan kiri. Tangan kanannya dirantai ke tiang besi.
“Dia dibawa pihak yang berwajib ke sini beberapa hari lalu karena ditemukan kelayapan di jalanan.”
“Kami tidak tahu nama pasien ini atau latar belakangnya karena ia jarang sekali bicara. Tapi sejak datang kelakuannya memang agresif,” kata Marsan.
Pasien yang agresif akan dilepas dari belenggu setelah lebih tenang, jelasnya.
Menurut Marsan, pihak yang berwajib sering membawa orang yang ditemukan berkeliaran di jalan ke pantinya.
Namun di awal pandemi ia berhenti menerima pasien baru karena takut mereka akan menularkan virus COVID-19.
Walaupun Al Fajar Berseri adalah lembaga swasta, Marsan mendapat bantuan dari pemerintah lokal.
Kepala Dinas Sosial Bekasi mengunjungi panti tersebut dua bulan sekali. Staf Puskesmas di dekat situ juga sering berkunjung untuk mengawasi kondisi pasien, kata Marsan.
Seiring dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19, pemerintah Indonesia berharap dapat melanjutkan kembali usaha mengakhiri praktik pemasungan.
“Kami akan meningkatkan jumlah layanan kesehatan jiwa berikut aksesnya, serta merancang program-program lintas sektoral,” kata Azhar dari Kemenkes.
Namun saat ini, Yasa masih terus terkurung di gubuknya di Karangasem. Hanya ibunya Seken yang menemani dan mendoakannya tiap hari.
“Saya berdoa agar Yasa sembuh dan jiwanya diselamatkan,” katanya.
Nama lengkap para ODGJ dan keluarga mereka telah disamarkan untuk melindungi identitas.
Baca artikel ini dalam Bahasa Inggris.
Baca juga artikel Bahasa Indonesia ini mengenai risiko keselamatan yang mengancam penambang intan Kalimantan.
Ikuti CNA di Facebook dan Twitter untuk lebih banyak artikel.